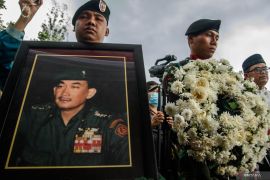Bocah yang baru menginjak kelas dua sekolah dasar itu memandangi serpihan hujan abu yang jatuh di lapangan rumput.
Ardi adalah salah satu dari sekitar 36.000 pengungsi korban letusan Gunung Merapi yang kini hanya bisa menunggu uluran tangan pemerintah, para dermawan, lembaga karitas dan donatur mancanegara.
Bersama pengungsi lainnya dia harus semakin menjauh dari puncak Merapi setelah Kamis malam (4/11) gunung yang di saat-saat normal memberikan sumber kehidupan itu memuntahkan awan panas dan lahar membara.
Sudah dua pekan Ardi bersama keluarga meninggalkan rumahnya di desa Kali Tengah Lor, hanya empat kilometer dari puncak Merapi.
Desa itu kini menjadi kawasan yang porak poranda. Rumah-rumah hancur, bahkan sebagian besar hangus tertimpa lava membara. Pohon-pohon besar tumbang, sapi-sapi dan ternak lainnya bergelimpangan.
Mereka sudah tiga kali berpindah dari satu lokasi penampungan pengungsi ke lokasi lain yang lebih jauh.
Kepindahan itu dilakukan seiring instruksi Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Surono untuk menambah radius zona bahaya Merapi.
Untunglah Ardi dan sebagian besar penduduk sudah meninggakan desa saat "wedus gembel" ( sebutan awan panas Merapi) dan lahar membara itu menimpa desa yang sebelumnya subur dan asri itu.
Tapi tak kurang dari 20 orang warga desa menemui ajal secara mengenaskan. Mayat-mayat mereka diangkut ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr Sarjito DIY Yogyakarta.
Sebagian besar korban hangus tak bisa dikenali lagi wajah mereka. Ada yang terbelah, ada yang kehilangan kaki dan kepala.
Setelah tak lagi memiliki tempat tinggal dan hidup di lokasi pengungsian, bocah yang gemar membantu sang ayah mencari rumput untuk ternak keluarga itu tampak murung.
Ketika ditanya soal keinginannya yang paling besar saat ini, Ardi bergumam lirih, "kembali ke sekolah".
Belajar kembali ke sekolah juga menjadi impian utama anak-anak lain di pengungsian Maguwoharjo. Ima (12), bocah dari Desa Pangkukrejo, Mumbulharjo, yang juga terguyur lahar Merapi bertutur:
"Saya senang kalau ada sekolah sementara di sini. Saya ingin mendengar cerita, bernyanyi bersama teman-teman."
Keinginan bersahaja dari seorang anak desa. Mendengar cerita dan bernyanyi bersama tentulah tidak memerlukan biaya besar. Itu hanya membutuhkan seorang yang bisa membaca buku cerita, dan memimpin anak-anak bernyayi bersama.
Di saat-saat normal, keinginan Ima itu bisa diwujudkan dalam hitungan hari, tapi di saat darurat seperti saat ini?
Tampaknya, hasrat mendengar cerita dan menyanyi bersama bisa menjadi sesuatu yang mewah di Maguwoharjo saat ini.
Pendidikan itu penting, tapi makanan untuk bertahan hidup masih lebih penting lagi. Puluhan relawan dari berbagai kalangan kini sibuk mengurus dan membagikan makanan kepada para pengungsi.
Mereka belum terpikir untuk menyelenggarakan pendidikan darurat di tempat pengungsian ini. Meski demikian, sudah ada beberapa penyumbang yang datang ke lokasi untuk membagikan buku tulis kepada anak-anak.
"Ya, kami baru bisa membagikan buku-buku tulis. Mudah-mudahan buku pelajaran sekolah segera ada yang menyumbangkannya," tutur Norma, seorang relawan yang juga mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Dalam busana muslim dan kerudung warna ungu, Norma lincah bergerak ke sana-kemari, kadang harus melompati orang-orang yang terlelap dalam posisi tak beraturan di lantai lorong Stadion Maguwoharjo.
Ia seperti tak pernah kehabisan tenaga mengurus jatah makan pengungsi, memberi nasihat pada ibu yang menangis karena salah seorang anggota keluarganya yang meninggal akibat lahar Merapi.
Di bagian bahu busana muslimnya, terdapat bercak kusam sisa tempias hujan abu.
Norma bertutur, pendirian sekolah darurat perlu segera diwujudkan. "Kami relawan sedang mengupayakannya. Mudah-mudahan ada dermawan yang bisa memfasilitasinya secepat mungkin," tambahnya.
Di lokasi pengungsian Maguwoharjo ini, ada lorong-lorong yang masih kosong, yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang-ruang kelas bagi anak-anak pengungsi. Jadi tak perlu mendirikan tenda-tenda sebagai ruang belajar.
Jika sekolah darurat itu terealisasi, bukan cuma anak-anak seperti Ardi dan Ima yang bersorak gembira.
Para orangtua juga memperoleh pelipur lara di tengah derita batin dan raga yang mereka alami
Inilah penuturan Slamet, seorang bapak tiga anak, yang rumahnya di Mumbulharjo, juga musnah oleh terpaan lava pijar: "Melihat anak-anak bisa belajar kembali membuat kami terhibur. Tanpa itu, kami khawatir akan larut dalam duka berkepanjangan."
Slamet bertutur, sebagian teman-teman sependeritaan dengannya, yang tak lagi memiliki apa-apa karena harta mereka musnah, kini mulai ada yang stres.
"Bahkan ada yang menangis. Saya sendiri pusing, sedang memikirkan apa yang akan saya kerjakan setelah bencana ini berakhir," tambahnya.
Selama ini, ketika hidup tenteram dan damai di lereng Merapi, Slamet bercocok tanam dan beternak. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang bersahaja.
"Ya, kami orang desa tak macam-macam kebutuhannya. Cukup pangan, sandang dan papan," ujarnya.
Ketika dilontarkan gurauan bahwa orang desa lebih kaya karena punya papan, sementara di kota banyak yang masih tinggal di kontrakan, Slamet hanya tersenyum sambil berkata lirih: "`Njenengan saget mawon. Ampun gojek, ah`". Maksudnya, "Anda bisa saja. Jangan berguarau, ah".
Di antara korban bencana Merapi yang kini tampak murung dengan mulut terkatup, Slamet adalah kontras di antara mereka.
Pria yang usianya baru kepala tiga ini memperlihatkan sisi optimisme. Meski sedang pening memikirkan apa yang bisa dilakukan kelak, Slamet percaya bisa bangkit kembali setelah desanya diluluh-lantakkan lahar Merapi.
"Biasanya, setelah enam hingga delapan bulan, lahar yang mematikan itu berubah menjadi pupuk alam yang menyuburkan. Ketika Merapi meletus empat tahun silam, enam bulan kemudian kami bisa bercocok tanam kembali. Hasilnya, sangat memuaskan. Pohon berbuah dengan kualitas super," tambahnya.
Tapi letusan Merapi kali ini tiga kali lebih dahsyat. Kerusakan yang ditimbulkan juga cukup meluas, semua sisi lereng Merapi, baik sisi Sleman, Madiun, maupun Klaten terimbas.
Seratus ribu orang dipaksa meninggalkan rumah. Angka-angka ini tidak banyak berarti seandainya korban Merapi kali ini memiliki sikap optimisme seperti yang dipunyai Slamet.
Optimisme atau harapan atau apapun namanya tentu hanya berarti jika pemerintah membuat kebijakan baru pascabencana Merapi. Minimal ada bantuan seperti pemberian bahan untuk pembuatan rumah sangat sederhana.
"Ada bantuan benih tanaman. Syukur-syukur kalau ada bantuan dalam bentuk induk ternak untuk kami gembalakan. Hasilnya bisa dibagi dua dengan pemberi bantuan," kata Slamet.
Slamet berharap pemerintah, dalam hal ini Pemda Sleman, akan membantu korban bencana Merapi bukan cuma saat ini saja, tapi juga pascabencana.
Tampaknya, harapan Slamet itu bukan sekadar harapan kosong. Sebab, sebelumnya Gubernur DIY Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang juga masih dipandang sebagai pemimpin sepantar raja, mengeluarkan instruksi pada jajaran aparat Pemda Sleman agar penanganan korban Merapi di wilayah itu menjadi fokus dan prioritas pembangunan di Sleman.
Artinya, Slamet dan rekan-rekan korban lainnya tak perlu cemas memikirkan masa depan. HB X sudah mengeluarkan titah pada bawahannya.
Dalam kosmologi Jawa, titah seorang raja dipandang setara dengan keniscayaan. Jika titah itu tak terlaksana, Slamet tinggal menagih janji. Soalnya adalah: bernyalikah "wong cilik" sekelas Slamet menagih janji kepada sang raja?
Ardi masih memandang hamparan rumput hijau lapangan bola. Tatapan mata seorang bocah yang lelah, sejak semalam dia belum bisa tidur pulas. Hujan abu masih mengguyur.
Malam nanti, dia tampaknya masih harus tidur dengan alas selembar tikar plastik yang tepiannya terburai. Tidur dalam kedinginan. Selamat malam, Ardi.(*)
M020/T010
Oleh Mulyo Sunyoto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010