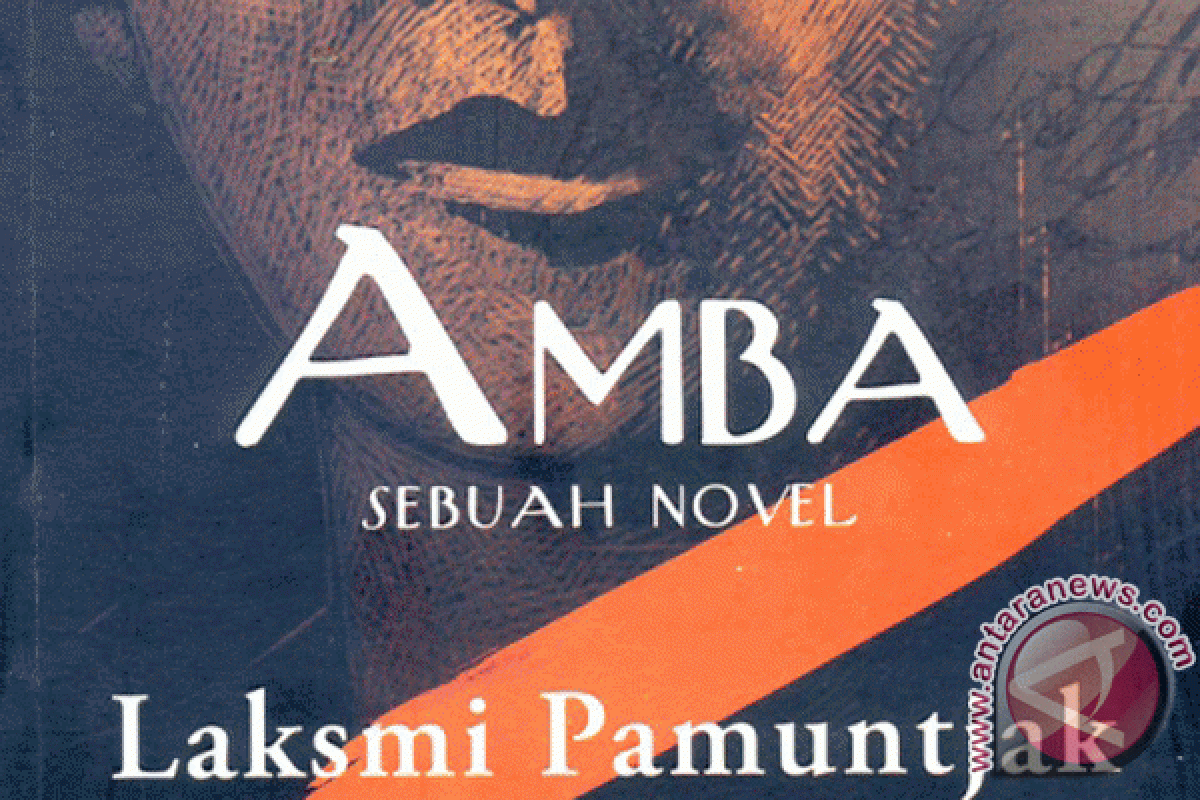Novel berstruktur penceritaan yang apik tersebut berlatar belakang Indonesia tahun 1965, yaitu masa yang boleh disebut salah satu bagian paling misterius dan mencekam dari sejarah bangsa ini.
Memotret para korban sejarah di atas para pemenang yang menuliskan sejarah bagai dogma putih melawan hitam, Laksmi menolak dikotomi ini karena pada setiap cerita kemenangan dalam sejarah, ada bagian besar yang diabaikan.
Laksmi mengilustrasikan ini dalam kutipan sajak Bertolt Brecht dalam dialog Bhisma kepada Amba --dua karakter utama dalam novel ini--, "Di tiap halaman tercatat kemenangan, tapi siapa yang memasak untuk pestanya?..tiap sepuluh tahun lahir orang besar, tapi siapa yang membayar ongkosnya."
Meski berpesan banyak, Laksmi menyembunyikan pesan-pesannya dalam
karakter-karakter novelnya ini --baik Amba, maupun Bhisma, Salwa, Samuel,
dan lainnya-- sehingga narasi novel tak gampang ditebak pembaca sebagai
"pesan" si pengarang seperti banyak ditemui pada novel-novel lain di
Indonesia.
Masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru biasanya menggoda pengarang untuk berpihak, namun Laksmi menyerahkan pembaca menjadi hakim untuk yang dibacanya, dan hanya berpesan tak ada yang absolut benar dan tak ada yang absolut salah.
Kendati kisah mengenai pencarian, cinta dan kesetiaan dominan, "Amba" lebih dari tema-tema itu.
Novel ini mengiris kerelatifan dogma yang kerap melulu soal memihak, sehingga diam menjadi derita besar manusia, seperti disebutkan Bhisma soal kegentingan pada masa utama dalam novel ini, "Diam memang menyakitkan...Terutama diam di tengah orang yang harus hidup dengan bunuh membunuh."
Masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru biasanya menggoda pengarang untuk berpihak, namun Laksmi menyerahkan pembaca menjadi hakim untuk yang dibacanya, dan hanya berpesan tak ada yang absolut benar dan tak ada yang absolut salah.
Kendati kisah mengenai pencarian, cinta dan kesetiaan dominan, "Amba" lebih dari tema-tema itu.
Novel ini mengiris kerelatifan dogma yang kerap melulu soal memihak, sehingga diam menjadi derita besar manusia, seperti disebutkan Bhisma soal kegentingan pada masa utama dalam novel ini, "Diam memang menyakitkan...Terutama diam di tengah orang yang harus hidup dengan bunuh membunuh."
Saat itu Indonesia amat terbelah. Kemerdekaan bukan hanya melahirkan
bangsa baru, namun juga perpecahan baru yang ditajamkan oleh perbedaan
politik.
Laksmi melukiskan atmosfer itu dalam suara hati Sudarminto, ayah Amba, "Sudah setahun lamanya, semenjak 1955, tahun Pemilihan Umum pertama, ada yang terasa licik dan berkhianat di udara...Di antara begitu banyak lambang yang harus dikenali (Kenapa partai harus punya lambang? Kenapa lambang harus punya arti yang lain?), orang telah memilih, seperti memilih kebenaran terakhir, dan tetangga dan keluarga saling menjauhi, atau menyesali, atau memusuhi, karena memilih partai yang tak sama".
Tak mendramatisasi
Laksmi menggambarkan kegentingan itu tanpa terlihat mendramatisasinya, tapi ironisnya
ini malah membuat pembaca membayangkan kedramatisan masa tersebut, dari
kegundahan Sudarminto di Kadipura sampai antiklimaks kebersamaan Amba dan
Bishma saat Universitas Res Publika diserbu.
Dalam alur terangkai rapi, Laksmi tak membiarkan bagian-bagian terpenting tertinggal, kendati pendedahan surat-surat Bhisma kepada Amba terasa menjemukkan dan memesankan imajinasi menyurut karena jalan cerita menjadi berliku.
Tapi Laksmi belumlah sampai pada tingkat ketika satu novel berakhir enteng atau dipaksakan berakhir, seperti umum ditemui pada novel-novel Indonesia, kecuali pada karya-karya Pramoedya Ananta Toer atau sekelasnya yang piawai meniadakan antiklimaks semacam itu.
Surat-surat itu sendiri mengungkap tautan hilang setelah insiden di Res Publika yang menjadi pertemuan terakhir Amba dan Bhisma. Di sini, Laksmi tak ingin memaksakan "cerita orang ketiga di luar tokoh-tokoh dalam novelnya" masuk sebagai jembatan untuk tautan hilang itu.
Di luar itu, "Amba" dibangun oleh riset panjang dan imajinasi mengenal batas sehingga cerita tak berubah irasional atau bahkan mistis.
Ada pesan pencarian kebebasan pada banyak bagian novel ini, tapi pencarian itu setiap kali membentur "kebiasaan" yang tak saja lahir dari praktik sosial, namun juga dikeraskan sebagai dogma, ideologi, bahkan diagamakan.
Novel ini juga memotret kegandrungan pada unsur-unsur baru dari luar yang melupakan konteks dan esensi sehingga acap mengantarkan pada pemahaman yang tak lengkap seperti tergambar dari isi surat Bhisma kepada kakaknya, Paramita, tentang orang-orang kiri yang ternyata mencampakkan kekritisan yang justru pengawal sosialisme, "...sosialisme tanpa kemerdekaan berekspresi apa jadinya?"
Dalam alur terangkai rapi, Laksmi tak membiarkan bagian-bagian terpenting tertinggal, kendati pendedahan surat-surat Bhisma kepada Amba terasa menjemukkan dan memesankan imajinasi menyurut karena jalan cerita menjadi berliku.
Tapi Laksmi belumlah sampai pada tingkat ketika satu novel berakhir enteng atau dipaksakan berakhir, seperti umum ditemui pada novel-novel Indonesia, kecuali pada karya-karya Pramoedya Ananta Toer atau sekelasnya yang piawai meniadakan antiklimaks semacam itu.
Surat-surat itu sendiri mengungkap tautan hilang setelah insiden di Res Publika yang menjadi pertemuan terakhir Amba dan Bhisma. Di sini, Laksmi tak ingin memaksakan "cerita orang ketiga di luar tokoh-tokoh dalam novelnya" masuk sebagai jembatan untuk tautan hilang itu.
Di luar itu, "Amba" dibangun oleh riset panjang dan imajinasi mengenal batas sehingga cerita tak berubah irasional atau bahkan mistis.
Ada pesan pencarian kebebasan pada banyak bagian novel ini, tapi pencarian itu setiap kali membentur "kebiasaan" yang tak saja lahir dari praktik sosial, namun juga dikeraskan sebagai dogma, ideologi, bahkan diagamakan.
Novel ini juga memotret kegandrungan pada unsur-unsur baru dari luar yang melupakan konteks dan esensi sehingga acap mengantarkan pada pemahaman yang tak lengkap seperti tergambar dari isi surat Bhisma kepada kakaknya, Paramita, tentang orang-orang kiri yang ternyata mencampakkan kekritisan yang justru pengawal sosialisme, "...sosialisme tanpa kemerdekaan berekspresi apa jadinya?"
Di sisi lain, kegandrungan pada hal-hal baru dipeluk dengan menolak dendam
lama. Laksmi melihat kekerasan 1965-1966 sebagian meletus karena dendam
lama ini.
Selain membuat kenaifan menjadi korban terbesarnya, dendam masa silam juga membuat bangsa ini gagal menyingkapkan apa yang sebenarnya berlaku dan kerap dibiarkan memantik konflik-konflik baru di kemudian masa.
"Amba" juga berisi ajakan berekonsiliasi dan jujur kepada masa lalu, selain mempertemukan lokalitas dengan kemoderenan seperti bahan-bahan masakan yang dipersatukan menjadi satu sajian rasa.
Uniknya, Laksmi adalah penulis kuliner dan dia tak ingin meninggalkan identitasnya itu tanggal dari novelnya, setidaknya lewat sisipannya tentang masakan pada bagian awal dan akhir cerita novel ini seolah memesankan bahwa hidup itu tentang masak dan masakan; tentang bahan, racikan, warna dan selera.
Ironisnya, sejarah kerap ditulis menurut warna dan selera; mengenai siapa yang mesti di-hitam-kan dan siapa yang harus di-putih-kan.
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014