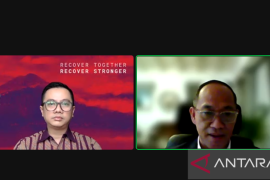Masalahnya, "perang dingin" itu tidak berlangsung terbuka, tetapi "memakai" Indonesia yang dalam hal ini adalah menyeret NU, Muhammadiyah, dan MUI dengan tuduhan yang sangat menyakitkan, yakni tokoh-tokoh Islam Indonesia itu telah "disuap" Tiongkok dalam persoalan Uighur (gratifikasi).
Tidak hanya itu, tuduhan kepada ormas Islam yang cukup besar di Indonesia itu "memakai" media massa yang memiliki kredibilitas, yakni WSJ, sehingga tuduhan yang mempertaruhkan kredibilitas itu ibarat pukulan telak yang tidak main-main dan bisa menggiring publik untuk percaya.
Tuduhan WSJ itu muncul pada laman WSJ edisi Rabu (11 Desember 2019) melalui artikel berjudul "How China Persuaded One Muslim to Keep Silent on Xinjiang Camps" yang menyebut NU, Muhammadiyah, dan MUI menerima gelontoran dana dari pemerintah Tiongkok untuk membungkam dan berubah sikap soal muslim Uighur.
Baca juga: Hidayat: Indonesia jangan hanya jadi penonton isu Uighur di China
Baca juga: FPKB: tudingan media Barat menyesatkan terkait muslim Uighur
Bagi Tiongkok, tuduhan WSJ itu membuyarkan upaya mereka dalam 3—4 tahun terakhir dalam membentuk opini tentang Uighur melalui pendekatan people to people dengan mengundang sejumlah tokoh agama, jurnalis/pimpinan media, dan akademisi dari Indonesia untuk "melihat langsung" apa yang sebenarnya terjadi di Uighur.
Betulkah media massa sekelas WSJ itu dapat dibenarkan dalam soal Uighur? Pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Namun, media massa yang memandang dari "ring luar", yakni ormas Islam di Indonesia atau tidak melihat langsung dari "ring dalam" melalui reportase ke Uighur itu berpotensi untuk bias.
Jurnalis kawakan Hersubeno Arif menegaskan bahwa media Barat tidak selamanya benar. Dalam kasus Asia Sentinel, media berbasis di Hong Kong itu terpaksa mencabut beritanya dan meminta maaf secara terbuka kepada mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.
Sebelumnya, Asia Sentinel menurunkan artikel yang mengaitkan pemerintahan SBY dengan skandal Bank Century. "Apakah WSJ akan bernasib sama dengan Asia Sentinel, atau mereka bisa membuktikan tuduhannya?" katanya, yang mengambil Muhammadiyah sebagai contoh.
Dari sisi kredibilitas, Hersubeno mencatat Muhammadiyah adalah ormas Islam terkaya di Indonesia. Mereka memiliki lembaga pendidikan sejak TK sampai perguruan tinggi. Pada tahun 2015 tercatat mereka memiliki 7.651 sekolah dan madrasah, dan 174 universitas, sekolah tinggi, institut, dan akademi.
Di bidang pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terdapat 457 rumah sakit, 318 panti asuhan, 54 panti jompo, dan 82 rehabilitasi cacat. Mereka juga memiliki sejumlah BMT, minimarket, dan koperasi. Dana likuid yang tersimpan di rekening mereka tercatat sebesar Rp15 triliun (2014).
"Jadi, tudingan mereka (Muhammadiyah) mendapat gelontoran dana dari pemerintah Cina, alias sogokan agar bungkam, adalah sangat merendahkan meski WSJ yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1889 di New York itu lebih tua daripada Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta, 18 November 1912," katanya.
Baca juga: Wapres Ma'ruf minta China lebih terbuka soal informasi Uighur
Pada masa jayanya, WSJ pernah menjadi koran terbesar di AS dengan oplah harian 2,6 juta eksemplar (2005). WSJ juga menerbitkan edisi Asia dan Eropa. WSJ dikenal dengan tradisi jurnalistik yang sangat kuat. Pilihan editorialnya cukup konservatif dan prudent. Bukan tipikal media yang bombastis seperti saingan utamanya, USA Today.
Sementara penulis artikel yang menohok itu adalah Jonathan (Jon) Emont koresponden WSJ yang berbasis di Hong Kong. Dia banyak menulis soal Uighur dan Rohingya. Sebelum bergabung dengan WSJ, wartawan yang fasih berbahasa Indonesia ini pernah tinggal di Jakarta. Dia menjadi koresponden freelance untuk sejumlah media yang sangat prestisius New York Times, Washington Post, dan Finacial Times.
Tinggal, bagaimana WSJ membuktikan akurasi tuduhannya, apalagi Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi yang menjadi salah satu dari 15 orang delegasi ormas Islam Indonesia beserta tiga wartawan nasional yang mengunjungi sejumlah kawasan di Xinjiang pada bulan Februari 2019 agaknya cukup kritis sehingga "mementahkan" tuduhan itu.
"Kehidupan Uighur yang ditunjukkan tampak banyak rekaan, terdapat sejumlah settingan sehingga Uighur tampak dapat mengekspresikan keagamaannya, padahal terjadi banyak pembatasan kehidupan Uighur," katanya.
Baca juga: Pemerintah China sebut Ozil dibutakan berita palsu soal konflik Uighur
Melihat Langsung
Sejatinya, pendapat itu tidak pernah tunggal, selalu ada dua versi atau bahkan lebih. Oleh karena itu, klaim atas kebenaran itu tidak alami (politis). Hal yang sama juga berlaku dalam menyikapi apa yang dialami etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok, karena apa yang dipersoalkan akhir-akhir ini sesungguhnya sudah terjadi sejak 1930 dengan versi realitasnya tersendiri. Bukan realitas kemarin sore.
Sebagai orang yang pernah melakukan "media visit" ke Tiongkok pada tanggal 2—11 Mei 2018, penulis membenarkan pendapat tokoh Dinasti Han Barat, yakni Zhao Chong, yakni bai wen bu ru yi jian yang maknanya sekali melihat sendiri itu lebih baik daripada seratus kali mendengar dari orang lain (kitab Han, susunan 32—92).
Pendapat Zhao Chong itu mengajarkan pentingnya melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi dengan "tahu/melihat langsung" dari versi realitas daripada mendengar dari orang lain dengan versi "laporan" dari pihak yang tidak datang langsung ke lokasi kejadian (laporan dari laporan).
Versi "laporan" tentang muslim Uighur yang cukup viral akhir-akhir ini seolah menjadi kebenaran tunggal, yakni etnis Uighur di Xinjiang mengalami pengasingan sehingga komunitas internasional, baik pers, tokoh politik, maupun lembaga kemanusiaan mengecam keras.
Bahkan, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan telah menerima laporan bahwa terdapat 1 juta etnis Uighur ditahan di suatu kamp pengasingan yang terselubung. Mereka dipaksa mengikuti program "Kamp Indoktrinasi Politik" yang di dalamnya diduga terdapat upaya pelunturan keyakinan yang dianut warga Uighur.
Baca juga: Lima juta muslim Uighur diperkirakan masih di kamp penampungan
Baca juga: ACT tentang pengungsi Uighur: Indonesia antipenjajahan
Laporan Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial yang berasal dari laporan pihak lain mencatat tindakan keji yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah menahan sekitar satu juta orang yang diduga berasal dari etnis Uighur di salah satu tempat kamp interniran (kamp pengasingan) berukuran besar, berjarak cukup jauh dari pusat kota Xinjiang.
Tidak hanya dari PBB, LSM HAM Amnesty Internasional dan Human Right Watch juga mengungkapkan laporan bahwa sejumlah etnis Uighur di Xinjiang dipaksa untuk bersumpah setia kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Mereka ditahan dalam lokasi penahanan besar tanpa alasan dan batas waktu yang diduga berada di area terpencil, yakni Dabancheng. Sebuah lembaga ruang angkasa multinasional bernama GMV menyatakan sedikitnya ada 101 fasilitas keamanan tingkat tinggi yang punya menara pemantau untuk mengontrol pergerakan siapa pun di dalamnya. Ini serupa dengan sebuah penjara raksasa.
Direktur Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa etnis Uighur mendapat perlakuan diskriminatif di Xinjiang, di antaranya larangan mengenakan hijab bagi perempuan di tempat-tempat publik, menumbuhkan jambang dan jenggot bagi anak-anak muda, berpuasa atau memiliki buku dan artikel dengan tema Islam.
"Amnesti Internasional mewawancarai 100 warga etnis Uighur untuk mengetahui situasi yang mereka hadapi. Hasilnya, ditemukan bahwa ada satu juta dari 11,3 juta etnis Uighur dimasukkan ke dalam Kamp Indoktrinasi Politik. Mereka dituduh sebagai ekstremis tetapi tidak ada bukti-bukti yang ditemukan. Kami menuntut pemerintah Cina memberikan penjelasan," kata Usman Hamid.
Realitas Tiongkok versi tunggal yang mengklaim kebenaran atas Uighur itu agaknya patut disandingkan dengan realitas di Tingkok (bai wen bu ru yi jian ). Dari pengalaman "melihat" RRT dalam "media visit" pada tanggal 2—11 Mei 2018 agaknya ada tiga kata kunci dalam "melihat" Uighur, yakni komunisme Tiongkok, kebebasan beragama dalam Konstitusi RRT (UUD), dan peta lokasi Uighur.
Baca juga: ACT salurkan bantuan bagi pengungsi Uighur di Turki
Khusus komunis, agaknya ada perbedaan pandangan, karena sebagian masyarakat Indonesia "melihat" komunis sebagai ideologi (pengalaman PKI 1965), sedangkan komunis bagi masyarakat Tiongkok hanya paham politik yang mendorong kesejahteraan masyarakat (ekonomi kerakyatan).
Bukti bahwa komunis di Tiongkok bukan ideologi adalah Konstitusi RRT yang menjamin kebebasan beragama bagi masyarakat, baik beragama atau tidak beragama. Realitasnya, Islam dan agama lain juga berkembang pesat di negara tersebut. Saat ini diperkirakan ada 38.000 masjid, termasuk gereja juga ada.
Terkait dengan peta lokasi Uighur yang perlu diketahui adalah kedekatan jaraknya dengan Afghanistan dan Pakistan yang selama ini juga santer diberitakan bahwa ada warga Indonesia berlatih perang atau "berjihad" di Afghanistan. Apalagi, warga Uighur yang sangat dekat jarak tempuhnya. Oleh karena itu, sangat mungkin kelompok radikal ada dalam etnis Uighur, bahkan disebut sudah ada sejak 1930.
"Saya sarapan pagi dengan muslim Uighur di hotel. Mereka bercerita kalau mereka aman-aman saja. Yang diperangi itu kelompok teroris, yang melawan pemerintahan yang sah. Namun, isu tekanan pada teroris itu dibawa oleh kelompok mereka yang sudah dibubarkan di Indonesia itu lewat media sosial," kata salah seorang pengurus NU NTB bernama Bahman Saputra. Dia sempat sedang bersilaturahmi dengan sejumlah muslim Uighur saat berkunjung ke sana.
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019