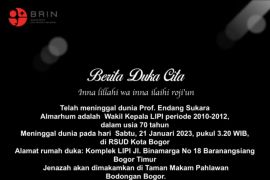rata-rata pengembangan obat memang plus minus sampai 10 tahunJakarta (ANTARA) - Fitofarmaka menjadi pilihan bagi negara seperti Indonesia dengan kekayaan hayati yang berlimpah. Dengan waktu pengembangan lima hingga 10 tahun dengan dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar dari mulai riset awal hingga jadi satu obat, valuasi ekonominya tentu.
Sebagai pembanding, untuk mengembangkan satu obat konvensional atau kimia single compound secara normal setidaknya membutuhkan waktu 20 hingga 30 tahun. Investasinya pun sangat besar dapat mencapai Rp50 miliar bahkan Rp100 miliar.
Perusahaan farmasi Indonesia mana yang mau melakukan riset obat single compound tersebut?
Mereka harus mencari DHA aktif dan harus mencari sintesisnya yang sesuai dengan pasar industrinya dan tidak perlu banyak langkah. Investasi pada tahap tersebut sangat besar, dan harus dilalui sebelum masuk tahapan selanjutnya mulai dari praklinik, clinical trial 1, clinical trial 2, clinical trial 3 yang keseluruhan hasil obatnya harus 100 persen aman bagi manusia.
Di Amerika Serikat maupun Eropa, obat yang dikembangkan sekarang ini harus memiliki kemampuan penyembuhan di atas obat-obat yang sudah ada di pasaran. Kalaupun yang sedang atau akan dikembangkan sama keampuhannya dengan yang sudah ada, Food and Drug Administration (FDA) mereka tidak akan menyetujuinya.
Begitu ketat untuk mengembangkan satu obat konvensional, karenanya melihat kekayaan leluhur menjadi alternatif.
Baca juga: Fitofarmaka, pilihan obat dengan kembali ke alam (1)
Baca juga: LIPI: Model bisnis berubah dalam hidup normal baru di tengah COVID-19
Riset fitofarmaka
Untuk mengembangkan satu fitofarmaka tentu perlu ada studi ilmiah guna mengetahui senyawa apa yang terkandung dalam flora ataupun fauna.
Setelahnya, studi in vitro dilakukan, baik dari bioassay hingga mekanisme aksi untuk mencari kandungan ekstrak ataupun senyawa tunggal yang ada pada tanaman.
Tahapan uji praklinis lalu dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktivitas senyawa itu pada mahluk hidup. Pada tahap itu, hewan-hewan uji laboratorium seperti mencit hingga primata yang memang bebas dari mikroorganisme patogen, memiliki reaksi imunitas yang baik, kepekaan pada suatu penyakit, dan performa atau anatomi tubuh yang baik yang berperan.
Saat uji praklinis dilakukan artinya proses trial and error terjadi. Kemampuan laboratorium diuji untuk mampu memastikan senyawa calon obat tadi aman untuk lolos ke tahap uji klinis, yang akan diujikan pada manusia.
“Tapi rata-rata pengembangan obat memang plus minus sampai 10 tahun. Itu terhitungnya sebagai obat konvensional, jadi yang single compound. Kalau obat herbal bisa lebih cepat, lebih pendek dari itu kalau kita sudah ada bukti empirisnya,” kata peneliti Centre for Drug Discovery and Development (CDDD) di Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mega Ferdina Warsito.
LIPI, menurut Koordinator peneliti pada Centre for Drug Discovery and Development di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Masteria Yonavilsa Putra, mencari atau eksplorasi senyawa aktif dari tanaman-tanaman obat atau dari laut Indonesia sudah sejak 20 hingga 30 tahun lalu. Tapi untuk tujuan pengembangan obat itu fokusnya baru lima tahun belakangan.
“Kita melihat global, dan kebetulan melihat kebutuhan dalam negeri. Tidak bisa juga karena globalnya perkembangannya seperti itu tapi di Indonesia tidak ada ya enggak bisa. Jadi kita lihat apa yang ada di Indonesia dan apa yang bisa untuk Indonesia,” ujar dia.
Baca juga: LIPI: Protokol baku-detail tiap sektor untuk hidup bersama COVID-19
Baca juga: LIPI kembangkan obat dan alat uji COVID-19 hingga solusi untuk UMKM
Kolaborasi
Namun demikian, perlu komitmen semua pihak untuk mengakselerasi perkembangannya di Indonesia, karena sejauh ini baru ada 18 fitofarmaka. Mulai dari komitmen pendanaan, regulasi, regulasi BPOM, regulasi Kementerian Kesehatan untuk uji trial semua mempengaruhi.
“Untuk uji trial itu kan perlu Kementerian Kesehatan karena mereka yang ‘punya’ rumah sakitnya. Kan enggak bisa kalau misal saya sudah punya obat tapi tidak bisa trial karena enggak punya pasien. Jadi memang sinergi semua pihak dan komitmen semua pihak penting,” ujar Masteria.
Untuk itu, sejak 2019, CDDD yang menggabungkan sejumlah pusat penelitian di LIPI untuk akselerasi memperoleh fitofarmaka dari herbal merah dan tripang pasir tersebut, katanya.
Sejauh ini tim sudah memiliki senyawa marker aktif yang mampu menghambat sel kanker dari tripang secara in vitro. Targetnya di 2023 sudah bisa menghasilkan fitofarmaka, jika tahap formulasi dan pengembangannya sesuai dengan regulasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Sinergi semua pihak diperlukan untuk dapat mempersingkat proses regulasi dan registrasi fitofarmaka. Dari Kementerian Kesehatan hingga BPOM, semua harus terlibat sejak awal penelitian itu berjalan, sehingga jika ada standar operasional prosedur (SOP) yang keliru dijalankan segera dapat dikoreksi sejak awal sehingga tidak perlu mengulang lagi dari permulaan.
Namun Masteria mengatakan komitmen menggenjot produksi obat di dalam negeri dengan menjadikannya Prioritas Riset Nasional harus diakui sangat membantu bagi para peneliti. Para peneliti tidak perlu lagi terbebani oleh urusan administratif, hanya fokus untuk riset sehingga output tercapai.
“Sekarang triple helix itu berjalan. Kita bahas terus setiap bulan, apa kendalanya. Ya tidak hanya LIPI karena ada universitas lain dan LPNK lain. Kita kolaborasikan dan elaborasi secara bersama,” ujar dia.
Hal lain yang tidak kalah penting, menurut peneliti dari Center for Drug Discovery and Development di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Siti Irma Rahmawati, memasukkan fitofarmaka hasil Prioritas Riset Nasional tersebut ke dalam e-katalog obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar obat tersebut terpakai.
“Itu penting, karena kalau tidak akan kalah bersaing dengan obat-obat konvensional. Dokter enggak mau meresepkan. Atau bisa masuk dalam e-katalog BPJS. Kenapa enggak bantu kita yang sudah melakukan riset dan memang sudah ada hasilnya, karena kalau tidak bisa dijual buat apa riset,” ujar dia.
Dengan memasukkannya dalam e-katalog JKN atau BPJS Kesehatan tentu masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya. Sehingga riset dan harapan Presiden Joko Widodo untuk mengupayakan pengurangan bahan baku obat impor berkurang sehingga harga obat menjadi murah tidak sia-sia.
Hal menarik lainnya terkait pertimbangan pengembangan fitofarmaka yang mungkin selama ini belum terpikirkan jika dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk menyembuhkan masyarakat terkena kanker yang menembus angka Rp13 triliun di periode 2014-2019.
Sementara dengan Rp5 miliar hingga Rp10 miliar dana riset pengembangan fitofarmaka untuk obat kanker dapat dilakukan dalam lima tahun misalnya, lalu setiap dokter mau meresepkan obat tersebut maka nilai miliaran rupiah yang telah dikeluarkan tentu tidak akan mubazir, kata Peneliti lainnya dari Centre for Drug Discovery and Development di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Iskandar Azmy Harahap.
Kepala LIPI Laksana Tri Handoko mengatakan keterlibatan swasta di tahapan pertengahan penelitian akan mempercepat Indonesia menghasilkan fitofarmaka.
"Jadi kita harus melibatkan swasta sejak di tahapan pertengahan, minimal setelah praklinis, sebelum uji klinis," katanya.
Swasta yang paling tahu kebutuhan pasar dan tentang mana obat yang lebih kompetitif sehingga dari beberapa kandidat fitofarmaka yang dikembangkan oleh peneliti bisa dipilih yang paling kompetitif nantinya untuk dipasarkan.
Setidaknya dalam dua tahun ke depan akan mulai banyak fitofarmaka yang memasuki tahap uji praklinis. Namun demikian, hal itu akan tergantung jenis obat yang hendak dikembangkan untuk bisa cepat menjadi fitofarmaka.
Baca juga: Peneliti: Tanaman hiperakumulator solusi bersihkan pencemaran lahan
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020