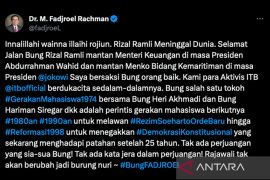... Pers memang dilahirkan untuk mewartakan kehidupan, termasuk episoda kematian yang menjadi bagian dari rentang waktu yang selalu ada ujungnya. Tak pernah ada pesta yang tak usai... Pada tanah itu jasad Ed menyatu kembali ke asalnya. Dari tanah kemPada tanah kuburan kecoklatan. Menerobos tegak nisan putih di antara hamparan warna-warni bunga makam. Rabu siang yang menyengat. Pada bagian atas nisan yang baru dipancangkan itu, terbaca nama Ed Zoelverdi bin Halim, yang ditulis tangan dengan kuas dan cat hitam.
Persis di bawahnya tertera Banda Aceh 12-03- 1943 Jakarta 4-01-2012. Sebentuk periode perjalanan waktu seorang anak manusia yang mewarnai samudra jurnalisme fotografi Indonesia dengan gayanya, sampai maut menjemputnya pada usia 68 tahun. Di ranjang gering, kediaman tetangga sekaligus sahabatnya, ibu Fatimah, yang meminjamkan ruang untuk perawatan Ed setelah sempat dirawat di RS Persahabatan, Jakarta Timur.
Perkabungan baru saja usai, satu persatu sejawat dan orang-orang tercinta pewarta foto kawakan tersebut berjalan gontai meninggalkan arena pemakaman di kawasan Pemakaman Kemiri yang letaknya tak jauh dari areal golf Rawamangun. Keharuan biru tertelan deru dan klakson kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Sekarang nisan bertuliskan nama Ed, tinggal sendirian di sana.
Aroma minyak wangi yang amat menyengat hidung menyeruak dari kerumunan bunga-bunga makam yang tadi ditaburkan segenap pelayat. Pada tanah itu jasad Ed menyatu kembali ke asalnya. Dari tanah kembali ke tanah. Jiwanya kini tenteram dalam keabadian nun tinggi di ufuk cakrawala infiniti sana.
Pemakaman insan pers pada usia senjanya, seringkali merefleksikan paradoks profesi jurnalisme dalam wajahnya yang hakiki. Suatu profesi yang ditempuh dalam hingar realitas penuh warna dan gairah reportase yang menembus kelas juga strata, melintasi batas-batas profesi yang ada dalam tatanan peradaban masyarakat.
Dari penguasa negeri hingga kehidupan bawah tanah yang perih. Pers memang dilahirkan untuk mewartakan kehidupan, termasuk episoda kematian yang menjadi bagian dari rentang waktu yang selalu ada ujungnya. Tak pernah ada pesta yang tak usai. Dalam prosesi pemakaman, baik kuli tinta dan juga kuli citra seperti Ed., selalu ada "reuni" keluarga besar pers. Semacam silaturahmi di antara pelayat pers yang masih hidup, seraya menebak-nebak siapa lagi di antara yang segera menyusul.
Ujung senja profesi ini nyaris selalu miris, seperti cahaya oncor yang terus meredup. Meskipun kita tahu kirana pantang padam, karena lorong jaman tak boleh dibiarkan gelap gulita. Dalam kerentanannya sekalipun segenap organisasi profesi pers yang ada di Tanah Air wajib menghapus pemeo yang menyebutkan kematian wartawan hanya mewariskan derita bagi keluarga yang ditinggalkannya.
Ed dalam karirnya di bidang fotografi jurnalistik jelas meletakkan pondasi visual bagi majalah Tempo yang diabdinya. Majalah berita yang berpengaruh dalam blantika pers nasional. Sebagai pribadi, Ed juga melengkapi karirnya dengan meluncurkan buku yang membuat kosa kata Mat Kodak menjadi sebutan lain untuk profesi pewarta foto.
Buku fotografi jurnalistik, Mat Kodak Melihat Untuk Sejuta Mata (112 halaman), yang diterbitkan Grafitipers pada 1985 adalah tonggak baru dalam blantika jurnalisme visual setelah imaji-maki sejarah dilakukan oleh Mendur Bersaudara dan IPPHOS menjadi pondasi awal fotografi jurnalistik modern Indonesia.
Mat Kodak mengisi kelangkaan referensi kepustakaan foto jurnalistik pada jamannya, apalagi yang ditulis oleh anak negeri. Ed meluncurkan buku perdananya pada karir emasnya. Satu dasawarsa berikutnya, Ed menjadi sumber utama fotografi jurnalistik di Tanah Air. Pribadi yang sangat terbuka pada generasi muda dalam membagi ilmunya.
Dalam bio di buku Mat Kodak dikisahkan, Ed adalah bungsu dari 10 bersaudara. Orangtuanya berasal dari Kotagadang, Bukittinggi. Sejak kecil dia telah tertarik dengan foto di suratkabar. Jadilah koran keluarga, Indonesia Raya, sebagai korbannya; karena Ed selalu memoraporandakannya dengan mengguntingnya untuk dijadikan kliping koleksi pribadi. Masih pada era 1950-an, Ed kecil mulai tertarik memindahkan citra foto di koran ke kertas dengan lilin, lalu pemberangusan Indonesia Raya dari tangan jahilnyapun terhenti.
Hijrah ke Jakarta. Ed lulus dari sekolah PSKD, sempat bekerja di Djakarta Lloyd 1962-1964, sebelum dia memutuskan menjadi pembantu lepas di sejumlah koran di Jakarta sejak 1965. Ed mulai masuk ke dunia pers sebagai ilustrator dan karikaturis (dia tertarik senil-lukis, sempat belajar pada Nashar dan Oesman Effendi) di harian Duta Revolusi, Djakarta Minggu dan di harian Kami. Di harian Kami, Ed mengembangkan karirnya sebagai penulis.
Dengan alias Batara Odin dan Matoari Ed mengasuh pojok khusus "Jangan Dilewatkan". Secara khusus Ed kemudian mulai berkenalan langsung dunia fotografi. Belajar otodidak. Kelak tulisannya di seputar fotografi pers muncul di Kompas, Sinar Harapan, Zaman, berkala Pers Indonesia, dan tentu saja Tempo.
Di Tempo, Ed bergabung sejak janinnya di Senen, 1971. Dua tahun sebelumnya dia sempat menjadi fotografer kontrakan untuk dokumentasi acara-acara di PKJ TIM. Di Tempo Ed berkelana dari desk ke desk. Pernah jadi Redaktur Foto, Redaktur Daerah-Kota, Pokok-Tokoh sebelum nangkring kembali sebagai Redaktur Foto. Kefasihannya menulis, kata Ed pada suatu ketika, dipoles oleh Goenawan Mohamad. Melalui bidangnya Ed sempat mengunjungi sejumlah negeri termasuk Jepang, Belgia, Belanda, Perancis, Ingris dan beberapa negara ASEAN.
Pada usia senjanya --setelah sempat bergabung dengan majalah Gatra -- sebagai redaktur pelaksana, Ed mulai memfokuskan mengajar fotografi jurnalistik di FISIP UI. Dia lalu memutuskan untuk mengontrakkan rumahnya di bilangan Mirah Delima, Sumur Batu, Jakarta Pusat, dan mengontrak rumah di Depok agar dekat dengan tempatnya mengajar di kampus UI. Sejak awal 2011, Ed tak lagi berani menyetir Mercy antiknya, karena matanya mulai rabun dan beberapa kali mengalami kecelakaan kecil karena faktor penglihatan itu.
Setelah itu kesehatan Ed yang perokok berat itu mulai menurun, dia dilarikan ke RS Persahabatan pada Desember lalu karena gangguan pernafasan yang akut. Majalah Gatra berkenan membiayai ongkos perawatan di sana. Sampai pada hari-hari ujungnya, saat dia kembali lagi ke kawasan Mirah Delima, kali ini di rumah tetangganya, yang juga sahabatnya, Fatimah.
Pada rumah itulah Ed mengikhlaskan jiwanya. Dia beristirahat di tempat yang dikehendaki Tuhan, bukan di lokasi yang dicita-citakannya, di Bukittinggi, Sumbar, kampung halamannya. Tempat di mana dia ingin membangun museum fotografi sekaligus menikmati hari tuanya dengan bahagia. (ANT)
(*) Oscar Motuloh, pewarta foto Kantor Berita ANTARA
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2012