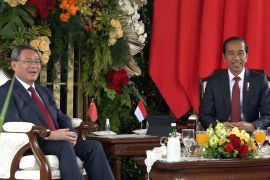Jakarta (ANTARA News) - Nama Wregas Bhanuteja melambung berkat karya film pendeknya Prenjak"/"In The Year of Monkey" (2016) yang memenangi Penghargaan Leica Cine Discovery dalam Festival Cannes 2016 di Prancis.
Setelah menggunakan musik latar instrumen tunggal piano dengan menggandeng Gardika Gigih dalam film pendek terdahulunya yang juga merupakan Tugas Akhir , "Lemantun" (2014), dalam "Prenjak" Wregas memberikan kepercayaan kepada Ragil Gregorius untuk menjadi penata musik yang menitikberatkan pada instrumen alat musik dawai gesek.
Baik Gigih maupun Ragil adalah pekerja kreatif yang masih berada dalam lingkaran pertemanan Wregas di kota ia tumbuh besar, Yogyakarta.
Berikut petikan bincang-bincang dengan sutradara yang sejauh ini telah menelurkan lima film pendek dan kerap terlibat dalam tim penggarap film arahan sutradara Riri Riza itu seputar musik latar film dan kepuasan berkarya:
Sepenting apa sebetulnya peran musik latar dalam sebuah film?
Ada semacam feel atau perasaan yang gak bisa tersampaikan dari film ke penonton jika itu hanya sekadar visual dan kata-kata. Jadi, gak bisa semua perasaan itu tersampaikan.
Misalnya gini, gua melihat Pakde di film Lemantun itu sebagai Pakde gua, tapi kan gua ada subjektivitas ketika melihat Pakde gua. Gua melihat Pakde gua itu semacam merasa kasihan dengan harus menjaga ibu di rumah. Itu kan pendapat subyektif saya.
Ketika saya cuma menampilkan di film secara gamblang dia seperti itu, penonton memiliki persepsi yang lain, "woh gak kasian kok pakde ini, gak seperti yang pakde rasakan, aku biasa saja memandang pakde ini," demikian.
Nah, satu hal yang bisa membantu mengarahkan penonton untuk bisa sepandangan dengan saya adalah musik. Musik itu bisa mewakili apa yang saya rasakan, apa yang saya pandang terhadap Pakde saya.
Menurut saya Mas Gigih, sebagai kakak kelas saya sewaktu SMA, itu bisa menangkap apa yang saya rasakan. Dia punya pendapat yang sama ketika memandang Pakdenya. Jadi ketika dia membuat musik, dia perdengarkan pertama kali itu saya gak perlu revisi lagi. Saya tinggal, "oke mas wis, wis apik". Tidak perlu ada revisi, ini sudah mewakili apa yang saya rasakan di hati saya ketika melihat Pakde.
Kalau untuk musik di Prenjak sendiri?
Ragil namanya. Prenjak ini membutuhkan sesuatu yang lebih keras. Kehidupannya tidak seromantis di Lemantun. Ini lebih keras, orang yang kepepet ekonominya. Dan menurut saya, musisi yang paling tepat untuk mengilustrasikan ini adalah Ragil, yang itu teman seangkatan saya juga sewaktu SMA.
Karena dia orangnya cukup keras. Dia punya karakteristik yang keras. Dia banyak mengalami penderitaan, paham apa artinya penderitaan. Jadi musik yang dia buatpun sedikit lebih menyayat dan tidak romantis.
Kalau Mas Gigih itu cenderung lebih yang happy, bahagia, cerah. Ibaratnya musik Mas Gigih itu terang. Ini tidak, Ragil lebih minor dan yang gelap. Saya membutuhkan semacam itu di Prenjak dan dia bisa menerjemahkannya dengan baik banget.
Dari dua penata musik ini masuk lingkaran pertemanan Yogyakarta, kemudian termasuk juga dalam kerja-kerja film terdahulu kru dan aktornya dari lingkaran pertemanan Yogyakarta, siapkah masuk ke dunia perfilman yang lebih profesional tanpa embel-embel kedekatan seperti itu?
Kebetulan saya terjun di industri film sejak tahun 2013 dan itu di Jakarta. Prinsipnya saya bisa bekerja sama dengan orang-orang profesional.
Saya bisa melakukan itu, tetapi ada hal yang tidak bisa didapatkan secara lebih dibandingkan jika bekerja sama dengan teman-teman Jogja. Ada privilege-privilege tertentu yang teman-teman Jogja berikan kepada saya yang membuat karyanya akan menjadi lebih spesial, akan menjadi lebih kuat. Tetapi secara standard kerja saya bisa kerja dengan siapapun, tetapi jika dengan Jogja ibaratnya feel atau taste-nya saya lebih masuk karena semuanya satu taste, satu visi.
Sama ibaratnya kalau kamu nge-band, kamu dipanggil nge-band di kafe ini bersama gitarisnya si A, B, drummernya si C yang tidak kamu kenal. Nge-ban ya udah tinggal baca not atau main sesuai irama, jadi. Tetapi kamu tidak merasakan feel-nya. Berbeda kalau kamu nge-band main jazz sama teman-teman yang sudah kamu kenal sedari kecil, eksplorasi bagaimanapun juga enak banget, mantap banget, seperti itulah rasanya.
Ismail Basbeth (sutradara "Talak 3", "Mencari Hilal" dan "Surga Yang Tak Dirindukan") pernah mengutip Hanung Bramantyo (sutradara "Jomblo", "Get Married" dan "?") bahwa sutradara berkualitas sudah waktunya berhenti berkarya hanya demi kepuasan sendiri, dengan begitu masyarakat punya pilihan film bagus di bioskop, menurut kamu bagaimana?
Prinsip gua gini, kalau secara pribadi gua bisa puas dan penonton bisa puas, kenapa gak begitu aja? Karena begini, seniman merasa puas terhadap filmnya ketika pendapat yang ada di dalam hatinya tuntas tersampaikan, betul kata Mas Ismail Basbeth tadi. Nah, ketika pendapat yang ada di hati gua itu ternyata kebetulan cocok dengan selera penonton, ya berarti gua puas, mereka puas. Begitu.
Seperti Lemantun. Lemantun adalah contoh yang paling kuat yang bisa saya ambil. Saya sebagai filmmaker puas sekali dengan film itu. Saya merasa penuh, merasa utuh dengan film itu. Tetapi penonton yang menyaksikan juga bisa ikut menangis, terharu, dan setelah pemutaran ada yang mendatangi saya dan bilang "saya terharu, saya ingin keluar dari rumah". Nah berarti saya berhasil di sini. Itu yang saya jaga.
Kebetulan apa yang menurut saya puas, apa yang memuaskan saya, bisa juga diterima oleh masyarakat.
Karena sebetulnya saya bukan tipikal sutradara yang mencapai kepuasan pribadinya dengan membuat film yang surealis atau sesuatu yang non-naratif atau bagaimana. Kebetulan apa yang saya bikin ternyata juga pas di hati penonton. Jadi kenapa aku harus mengorbankan kepuasanku.
Jadi tetap memperhatikan kepuasan pribadi?
Tetap saja.
Di semua filmmu selalu mencatumkan ucapan terima kasih kepada Riri Riza, tentunya selain terlibat dalam "Ada Apa Dengan Cinta 2" (2016) ada pelajaran apa saja yang didapat dari Riri Riza?
Gua selalu menganggap dia itu guru.
Gua pertama kali magang di layar lebar itu juga di "Sokola Rimba" (2013) bareng Mas Riri sebagai Astrada (Asisten Sutradara) 3 waktu itu. Terus habis itu proyek-proyek film MiLes berikutnya gua terlibat termasuk "AADC 2" ini. Gua tumbuh besar dengan film-film dia. Gua nonton semua film-film dia, mulai dari "Gie" (2005), "3 Hari Untuk Selamanya" (2007), "Petualangan Sherina" (2000), gitu-gitu ya.
Dan gua selalu menganggap dia guru, termasuk di tempat syuting pun ketika seorang pemain berakting dan Mas Riri men-direct-nya bahwa lirikan mata itu sangat berarti. Misalkan ketika dialog gini nih, terus mata lo ngelirik sedikit saja itu sudah memberikan arti yang berbeda. Itu penting banget fokus mata harus dijaga. Bagaimana shot itu harus ditata, di-copas dari mana itu semua gua belajar banyak dari dia.
Tinggal bagaimana gua meng-combine itu semua dengan jati diri gua. Mas Riri banyak bikin film tentang Indonesia yang itu di luar pulau, di Sumba mungkin atau di Atambua gitu ya. Nah gua meng-combine itu dengan apa jati diri gua, yaitu Jawa. Gua meng-combine itu dengan apa yang gua tahu.
Selain Riri siapa sineas idola dan panutan?
Ada, dua-duanya sudah almarhum. Yang satu almarhum Asrul Sani, yang satu almarhum Teguh Karya.
Dari tiga sineas itu, film-film favorit karya mereka apa?
Asrul Sani judulnya "Apa jang Kau Tjari, Palupi?" (1969). Dari Pak Teguh Karya, "Secangkir Kopi Pahit" (1985). Mas Riri, "Eliana Eliana" (2002).
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016