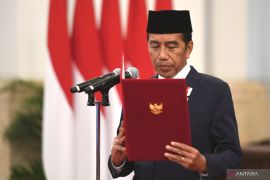Presiden menambahkan, salah satu dampak terbesar krisis iklim adalah krisis pangan, yang hari-hari ini sudah mulai terjadi. Presiden menyampaikan peringatan ini pada Festival LIKE (Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi EBT) Road to COP (KTT Perubahan Iklim).
COP 28 tahun ini akan diselenggarakan di Dubai (UAE ), akhir November sampai awal Desember 2023.
Dalam acara yang sama, Presiden memberikan saran, melakukan transisi menuju ekonomi hijau secara global. Aktivitas hijau seperti daur ulang sampah, industri hijau, produksi kendaraan listrik, hingga pemanfaatan bahan bakar hijau, kini harus diupayakan secara masif, termasuk Indonesia.
Sebagai pemangku kepentingan garda terdepan sektor energi, terutama PT Pertamina (Persero), bisa memberikan kontribusi signifikan, sebagai bagian dari mitigasi dampak krisis iklim. Dunia harus berkolaborasi lebih efektif dalam mitigasi dan adaptasi iklim menghindari “kerusakan ekologis” dan pemanasan global yang berkelanjutan.
Dalam sejarah modern, umat manusia telah menghindari beberapa depresi besar, salah satunya merancang vaksin untuk menghentikan penyakit dan menghindari perang nuklir. Inovasi juga memungkinkan manusia untuk menguasai krisis ekologi dan perubahan iklim di masa depan.
Kolaborasi global
PT Pertamina (Persero) bersama sejumlah korporasi global yang sejak lama beroperasi di Indonesia, memang telah menyatakan komitmen untuk memanfaatkan energi terbarukan (renewable energy) secara masif.
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ambisius adalah bentuk kontribusi korporasi tersebut, guna mendukung target miminal 50 persen EBT dalam bauran energi nasional pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun RI kelak.
Korporasi global dimaksud antara lain adalah Amazon, Nike, NB (New Balance), Schneider, Danone, dan lain-lainnya. Komitmen sejumlah korporasi multinasional tersebut, diharapkan bisa menjadi stimulan bagi partisipasi sektor swasta lain di tanah air dalam antisipasi perubahan iklim.
Komitmen itu difasilitasi oleh Clean Energy Investment Acceletator (CEIA), organisasi internasional yang mendorong akselerasi transisi energi , khususnya di negara berkembang dengan memiliki pangsa pasar listrik skala besar, seperti Indonesia.
Keterlibatan korporasi global dan organisasi independen seperti CEIA, merupakan sinyal tentang betapa besarnya perhatian komunitas pemerhati isu lingkungan internasional, terhadap upaya pemerintah RI dalam mitigasi dampak perubahan iklim.
Mitigasi perubahan iklim akan terlampau berat bila hanya ditanggulangi sendiri oleh pemerintah, sehingga dibutuhkan partisipasi aktor non-negara, seperti LSM, lembaga riset, akademisi, perguruan tinggi, sektor industri, sektor bisnis, dan lain-lain. Fungsi pemerintah dibutuhkan dalam konteks regulasi, kebijakan, dan mendorong sinergi.
Dalam kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI, kemampuan negara dalam pendanaan mitigasi perubahan iklim masih terbatas atau hanya sekitar 34 persen dari yang seharusnya dibutuhkan. Itu sebabnya pelibatan sektor swasta menjadi krusial.
Selain aspek pendanaan, sektor swasta dikenal memiliki kompetensi teknis dan efisiensi, yang bisa mendukung program mitigasi dampak (termasuk adaptasi) krisis iklim.
Ada nilai tambah bagi sektor swasta ketika berpartisipasi dalam upaya mitigasi pemanasan global, yaitu meningkatnya citra jenama (merek) sebagai bisnis yang ramah lingkungan.
Aspek lingkungan dan ketersediaan sumber energi terbarukan, akan menjadi pertimbangan korporasi atau investor dalam menanamkan investasinya di suatu negara, dan akan menjadi tren pada masa mendatang.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan kemitraan lintas sektoral, utamanya dengan sektor swasta.
Keterlibatan sektor swasta di negeri kita dalam isu perubahan iklim sudah dimulai dengan pembentukan asosiasi Indonesia Bussiness Council for Sustainable Development (IBCSD ) sejak tahun 2017.
Korporasi global dan sektor swasta memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengembangan teknologi, model bisnis, dan layanan yang bisa digunakan masyarakat (end user), untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang rendah emisi dan tahan iklim.
Sementara pemerintah dan lembaga riset, dalam posisi sebagai katalisator dan pemandu, dalam upaya sektor bisnis untuk berinovasi dalam teknologi iklim.
Salah satu panduan atau supervisi yang bisa dilakukan pemerintah, bagaimana mengelola program Corporate Social Responsibility (CSR), agar dalam implementasinya memiliki kesesuaian dengan isu ramah lingkungan dan transisi energi.
Program CSR salah satunya bisa digunakan untuk dana riset, mencari solusi mengatasi kendala dalam pengembangan kendaraan listrik, tentu bagi korporasi yang relevan.
Kendala dimaksud adalah dalam penguasaan teknologi, utamanya industri baterai sejak di hilir, durasi daya baterai, kecepatan pengisian daya, termasuk pemanfaatan limbah baterai.
Dalam tinjauan Organization for Economic Cooperation and Development/ OECD (2022) guna menghadapi perubahan iklim, dibutuhkan transformasi ekonomi dan sosial yang berjangkauan luas, dan sektor swasta memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi iklim, yang dapat membantu masyarakat mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan perubahan iklim.
Dengan dorongan, panduan dan kebijakan yang tepat, pengusaha dapat menyalurkan upaya mereka secara efektif untuk mengembangkan solusi ramah iklim.
Sektor swasta butuh insentif untuk mengeksplorasi peluang inovasi di bidang teknologi iklim. Pemerintah melalui otoritas lokal dan nasional, mungkin dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada pengusaha. Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang yang dibuat oleh semua negara untuk menjaga suhu bumi sesuai Kesepakatan Paris, yang muncul saat COP 21.
PLTP sebagai backbone
Merujuk Kesepakatan Paris (2015), peningkatan rata-rata suhu global disepakati agar ditahan pada angka 1,5 derajat celsius, sebagai cara menghindari ancaman krisis iklim, sebagaimana disebutkan di awal tulisan.
Indonesia sendiri berkomitmen untuk memenuhi target emisi nol bersih (net zero emissions, NZE) pada 2060, atau lebih cepat. Juga melalui enhanced nationally determined contribution (NDC), yakni pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43, 2 persen dengan bantuan internasional pada 2030.
Untuk mendukung program tersebut, Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), tidak berhenti mengembangkan energi terbarukan, dalam hal ini pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Sejumlah PLTP telah beroperasi, salah satunya adalah PLTP Lahendong (Sulut), yang dikelola oleh PGE, yang menjadi tulang punggung dalam memasok kebutuhan energi di Sulut dan Gorontalo.
PLTP Lahendong juga menjadi salah satu kontributor rencana PGE untuk meningkatkan kapasitas terpasang total, dari saat ini 672 MW menjadi 1 gigawatt (GW). Dari berbagai jenis energi terbarukan, salah satu yang sudah tereksploitasi dan keandalannya teruji, adalah panas bumi.
Dari sejumlah PLTP yang telah beroperasi di Indonesia, sesuai data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTP meningkat dari 1.948,3 MW pada 2018, menjadi 2.355,4 MW pada 17 wilayah kerja panas bumi (WKP) pada tahun 2022.
Hingga semester I-2023, kapasitas terpasang PLTP mencapai 2.373,1 MW atau di atas target 2023 yang 2.368,4 MW. Menteri ESDM Arifin Tasrif memperkirakan, Indonesia membutuhkan listrik sebesar 1.942 terawatt-jam (TWh) pada 2060.
Salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan itu terkait penyediaan listrik dari sumber energi terbarukan, yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan. Hal itu dapat dipenuhi antara lain, dengan memanfaatkan panas bumi. Pemerintah mematok target, kapasitas terpasang PLTP sebesar 22 gigawatt pada 2060.
“Untuk meningkatkan pemanfaatan energi bersih, Indonesia akan membangun sekitar 700 gigawatt (GW) pembangkit listrik energi terbarukan. Mengingat Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah, potensinya mencapai lebih dari 3.600 GW,” kata Menteri ESDM kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Selaras dengan program strategis nasional dalam optimalisasi pemanfaatan kendaraan listrik, Pertamina telah menempatkan stasiun pengisian energi listrik untuk kendaraan listrik berbasis baterai (EV charging station), pada sejumlah titik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pemasangan EV charging station merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mengembangkan energi berkelanjutan.
Dalam transisi energi, untuk mencapai target bauran energi terbarukan, tidak semua harus beralih menggunakan kendaraan listrik. Ikhtiar lainnya bisa dengan menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan (energi hijau). BUMN dalam posisi ini menjadi pendukung utama dalam program dekarbonisasi sektor transportasi.
*) Dr Taufan Hunneman adalah Dosen UCIC, Cirebon.
Copyright © ANTARA 2023