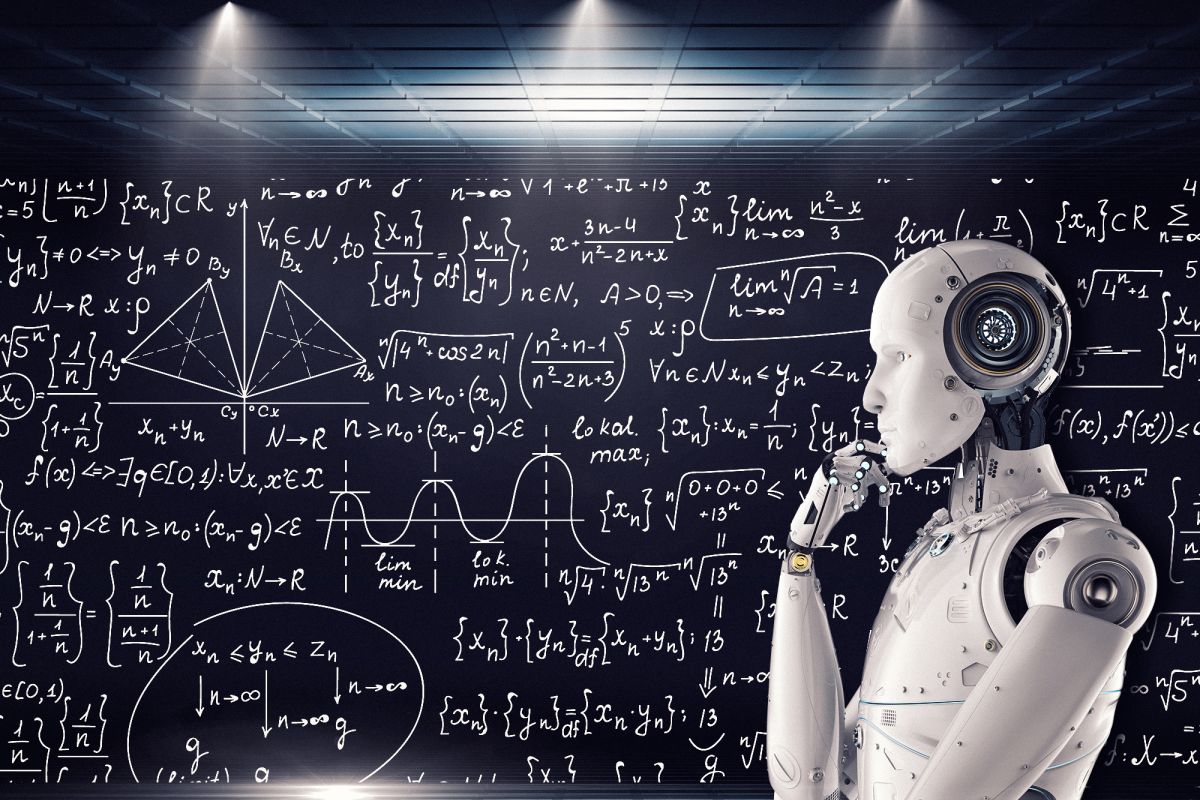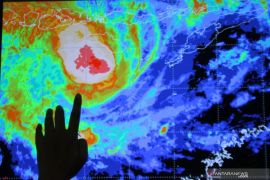Memang, untuk saat ini, hal itu belum lazim, tapi praktik kerja semacam itu bisa saja umum pada masa mendatang ketika kemampuan Generative AI semakin maju.
Selain hoaks, AI adalah subjek yang ramai diperbincangkan dalam pelbagai forum dan diskursus global mengenai jurnalisme sepanjang tahun ini, termasuk dalam kongres tahunan Asosiasi Wartawan Eropa (AEJ) di Albania dan World Media Summit di Guangzhou, China, pada 1-7 Desember.
AI diperbincangkan karena potensinya dalam mengubah drastis pola produksi, konsumsi, dan bisnis berita.
"Tak lama lagi cara kita membuat berita akan berubah drastis, begitu pula cara orang mengonsumsi berita, dan hubungan antara brand dan audiens," kata Kepala Kantor Berita Reuters Sue Brooks di Guangzhou, beberapa waktu lalu, seperti dikutip Kyodo.
Tetapi AI juga menjadi ancaman bagi dunia jurnalistik dan bisnis media, selain menciptakan dilema moral dan etika.
Salah satu yang dikhawatirkan adalah relasi AI dengan kebenaran. AI berpotensi meredefinisi kebenaran ketika pada masa post-truth seperti sekarang orang semakin sulit membedakan antara informasi yang benar dan tidak.
Situasi ini bisa semakin pelik jika AI memilah dan mengembangbiakkan informasi dari miliaran data dalam "big data" secara tidak benar.
Hal itu dimungkinkan karena digitalisasi membuat kebenaran ditentukan oleh informasi terpopuler, menurut algoritma.
Ini karena algoritma cenderung lebih memilah informasi bukan dari benar dan salah atau baik dan buruk tentang sesuatu hal, melainkan dari informasi terbanyak mengenai sesuatu hal itu.
Didikte algoritma
Bagi pihak yang melihat otomatisasi sebagai kesempatan untuk menciptakan proses produksi yang lebih murah, tapi mendatangkan keuntungan lebih cepat dan lebih besar, AI adalah peluang besar.
Situasi itu semakin didukung oleh ekosistem bisnis media saat ini yang memberikan ganjaran lebih besar kepada konten sederhana tapi populer, ketimbang konten yang dihasilkan dari proses panjang dan mahal, tapi bernilai tinggi, seperti liputan investigatif.
Situasi ini mendorong banyak media mengakali keadaan dengan memancing orang mengklik konten dengan judul sensasional, namun isinya tak mencerminkan judul (clickbait).
Tapi clickbait sendiri lahir dari ekosistem media yang sudah amat ditentukan oleh algoritma yang memperingkat konten lebih berdasarkan pada popularitas, ketimbang salah satu benar, baik atau buruk.
Petunjuk untuk kecenderungan itu bisa dilihat dari sumber lalu lintas web pada laman-laman berita, termasuk di Indonesia, yang umumnya tergantung pada organic search atau organic traffic (kunjungan lewat mesin pencari) di mana peran algoritma sangat dominan.
Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang dibuat laman penganalisis situs web, Similarweb, periode September-November 2023, kebanyakan laman berita mengandalkan organic traffic di atas 60 persen dari total traffic.
Bersama direct search atau direct traffic (kunjungan langsung ke laman berita), organic traffic adalah sumber utama lalu lintas web. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan.
Direct traffic tak begitu terpengaruh perubahan algoritma, sebaliknya organic traffic dipengaruhi algoritma mesin pencari.
Organic traffic ini baik untuk menarik audiens baru dan membangun kredibilitas, sedangkan direct traffic menjadi petunjuk untuk kuatnya brand media dan loyalitas pengguna konten media.
Dari data Similarweb, hanya laman-laman seperti Detik.com dan Kompas.com yang memiliki proporsi direct traffic yang besar, masing-masing 43,06 persen dan 35,09 persen, sedangkan kebanyakan media lain di bawah 30 persen.
Pola bisnis kacau
Direct dan organic traffic memang sama penting, tapi lebih bagus jika seimbang karena dengan cara itu media bisa lebih menjaga kualitas produk tanpa mengganggu profitabilitas finansial media itu.
Tapi untuk sampai ke level itu, butuh infrastruktur teknologi, sistem pemasaran, dan struktur keuangan yang kuat. Masalahnya, tak banyak media yang memiliki modalitas seperti ini.
Sebaliknya, keterbatasan modalitas membuat media menjadi pragmatis dengan menuruti "diktasi" algoritma yang salah satu akibatnya mendorong media kian sering menghasilkan konten-konten clickbait, entah teks, audio, atau video.
Ini persoalan besar media, tapi media tak bisa mengatasinya sendirian, karena tak ada yang bisa mendesak Google, TikTok, Meta, dan lainnya untuk membuka algoritma mereka.
Yang bisa dilakukan media hanyalah menaksir pola pencarian internet dengan optimalisasi mesin pencari (SEO).
Di sisi lain, mesin pencari dan media sosial telah mengacaukan pola bisnis media. Mereka mendapatkan konten dari media, tapi media tak mendapatkan keuntungan finansial signifikan dari mereka.
Inilah hal yang dikritik oleh banyak kalangan di beberapa negara, termasuk di Australia.
Pada 2021, Australia membuat terobosan dengan mensahkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan-perusahaan mesin pencari dan media sosial membayar fee kepada perusahaan media untuk setiap konten yang mereka gunakan.
Awalnya, prakarsa ini ditentang, terutama oleh perusahaan-perusahaan raksasa teknologi (Big Tech), seperti Meta yang menjadi perusahaan induk Facebook dan Alphabet Inc yang beranak perusahaan Google. Namun, UU itu akhirnya mulus dipraktikkan di Australia.
Ternyata, menurut Profesor Rod Sims dari Australian National University dalam Los Angeles Times pada 7 Uni 2023, setelah dua tahun menerapkan UU itu, perusahaan-perusahaan media Australia mendapatkan tambahan pemasukan 140 juta dolar AS (Rp2,16 triliun) per tahun yang cukup untuk membuka rekrutmen wartawan baru dalam jumlah besar.
Perlindungan lengkap
Cara Australia bisa ditiru oleh siapa pun, termasuk Indonesia, tapi tantangan media yang kian pelik setelah kehadiran AI, membuat perlindungan tak cukup dengan mengharuskan Big Tech membayar fee kepada perusahaan media.
Kini semua pihak perlu mencari dan menyiapkan cara menyiasati invasi AI yang diyakini akan kian luas.
Sejumlah media menyiasatinya dengan membuat panduan etik untuk penggunaan AI seperti ditempuh Associated Press dengan menerbitkan pedoman AI.
Associated Press menyatakan tool AI tak bisa digunakan untuk membuat konten tersiar, namun kantor berita Amerika Serikat itu menganjurkan wartawan-wartawannya mengakrabi AI.
Langkah menghadapi invasi AI juga bisa dilakukan oleh negara.
Saat ini sejumlah negara telah dan tengah membangun benteng hukum dan etika yang tak hanya melindungi jurnalisme, tapi juga banyak aspek kehidupan.
Intinya, tantangan media yang kian berat membutuhkan pedoman internal, dan proteksi eksternal dari sistem kebijakan.
Perlindungan internal bisa dilakukan dengan cara seperti diadopsi AP, sedangkan perlindungan eksternal bisa ditempuh dengan merangkul cara Australia atau panduan legal yang dibuat Uni Eropa.
Perlindungan ini di antaranya demi menyediakan ruang lapang bagi media untuk berkreasi dalam menjaga kualitas produk yang antara lain penting dalam memerangi hoaks dan disinformasi.
Copyright © ANTARA 2023