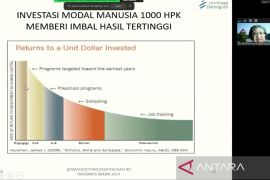Sosiolog terkemuka dalam dunia keilmuan sosial di Tanah Air, Selo Soemardjan, menulis bahwa ciri seorang cendekiawan antara lain mencintai kesenian.
Itu sebabnya cendekiawan yang bidang keahliannya matematika pun tidak menutup kemungkinan baginya untuk mencintai sastra atau seni rupa.
Dari sudut pandang peran yang dimainkannya, Wikipedia memaknai cendekiawan atau intelektual sebagai orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, atau menyoal dan menjawab persoalan.
Dari dua landasan teoritis tentang makna kecendekiawanan di atas, ada poin inti yang mau dikatakan di sini bahwa sifat kecendekiawanan menyangkut dua aspek, pertama, tentang minat pada dunia seni dan kedua, kesanggupannya untuk menjawab berbagai persoalan.
Apakah guru-guru, baik di jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, maupun menengah atas, sebagian besar sudah memiliki sifat kecendekiawanan itu?
Riset tentang hal ini belum pernah terdengar dilakukan di lingkungan guru. Namun, secara kasus per kasus dapat dikatakan bahwa ada guru-guru yang mempunyai karakter seorang cendekiawan.
Tentu jumlahnya belum bisa dibilang mayoritas. Adanya guru matematika yang ikut terlibat memikirkan dan memublikasikan pikirannya dalam memecahkan problem sosial, seperti kenakalan remaja, gejala geng motor, membuktikan bahwa guru tersebut memainkan peran seorang cendekiawan.
Dalam kebijakan pendidikan yang kini ditekankan pada penguatan pendidikan karakter siswa, pembentukan kecendekiawanan guru agaknya menemukan urgensinya.
Seperti dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy belum lama ini bahwa hakikat guru sebagai pendidik akan dikembalikan dalam praksis pendidikan di Tanah Air.
Pernyataan Mendikbud itu terkait dengan program sekolah lima hari dengan modus penyelenggaraan pendidikan delapan jam sehari.
Guru-guru, demikian kata Muhadjir, perlu ditingkatkan porsinya sebagai pendidik dan bukan sekadar pengajar di sekolah.
Seorang pendidik tentu dituntut mempunyai komitmen untuk ikut menyelesaikan atau menjawab tantangan yang dihadapi murid-muridnya. Komitmen semacam itu sejalan atau pararel dengan tuntutan komitmen dari seorang cendekiawan.
Dalam perspektif historis, dunia mengenal banyak ilmuwan yang memainkan peran sebagai seorang cendekiawan yang bisa dimetaforakan sebagai obor atau panduan hati nurani rakyat.
Contoh yang paling fenomenal adalah ilmuwan fisika nuklir Andrei Dmitrievich Sakharov dari Soviet yang pada 1975 dianugerahi Nobel Perdamaian.
Shakarov tak cuma berkutat dengan teori-teori fisika nuklir tapi dia juga menyuarakan hati nuraninya untuk kepentingan hak-hak sipil, kemerdekaan berpendapat, dan pembaruan sistem politik di negerinya yang dikuasai kaum tirani.
Guru yang bermental cendekiawan juga dituntut tak apatis terhadap persoalan di luar bidang ilmu yang ditekuninya. Masalah-masalah personal kemanusiaan yang sedang dihadapi siswa tentu membutuhkan pemecahan dari seorang guru yang berjiwa cendekiawan.
Bagaimanakah jalan untuk mencapai karakter cendekiawan itu? Apa yang harus dilakukan seseorang yang sejak awal berminat menjadi guru dan sekaligus menyandang predikat cendekiawan?
Tentu jalan paling utama adalah memperluas sekaligus memperdalam pengetahuan, mencintai hal-hal yang bersangkut paut dengan kesenian. Dengan demikian, meskipun anda, misalkan menjadi seorang guru olahraga atau fisika, ada baiknya anda adalah seorang pembaca sastra serius, membaca dan mengikuti perkembangan sosial-politik yang sedang berlangsung.
Apa manfaat membaca semua itu? Tentu manfaatnya akan terasa ketika akumulasi pengetahuan itu mengendap di batin seseorang dan digunakan untuk memecahkan persoalan riil yang substansinya pernah jadi tema inti bacaan tersebut.
Dengan banyak membaca buku-buku sastra serius, yang merupakan hasil refleksi sang pengarang terhadap berbagai persoalan riil keseharian maupun persoalan spekulatif metafisik, seorang guru akan mempunyai bekal pengetahuan yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah yang dihadapi siswa bila masalah itu bersinggungan dengan tema bacaan tersebut.
Kenapa bacaan sastra disarankan sebagai salah satu peranti untuk membangun mental kecendekiawanan? Apa yang pernah dikatakan kritikus sastra Dami N Toda agaknya bisa menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut.
Dalam salah satu esai yang ditulisnya, Dami mengatakan seorang sastrawan cendekiawan selalu bereaksi terhadap berbagai persoalan manusia. Persoalan itu bisa berupa korupsi, kemiskinan, pengkhianatan, penindasan, penyelewengan, penderitaan.
Guru-guru yang banyak membaca persoalan-persoalan itu lewat karya sastra tentu akan mempunyai banyak bahan untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan yang menimpa siswanya.
Buku-buku sastra serius karangan Mochtar Lubis seperti Jalan Tak Ada Ujung, cerpen-cerpen Ali Akbar Navis yang terkumpul dalam buku Robohnya Surau Kami atau karya-karya Pramoedya Ananta Toer seperti Korupsi, Arus Balik patutlah dijadikan bahan pertimbangan guru untuk dibaca.
Guru-guru juga bisa memperluas horizon bacaan sastra mereka dengan menyimak karya-karya pengarang mancanegara, seperti Madame Bovary oleh Gustav Flaubert, Kisah Dua Kota oleh Charles Dickens, dan Dokter Zhivago oleh Boris Pasternak.
Buku-buku klasik itu kini dicetak ulang, dijual di toko-toko buku dan bisa dijadikan pilihan oleh para (calon) guru muda yang hendak memupuk jiwa kecendekiawanan mereka.
Dengan demikian, ikhtiar Mendikbud mengembalikan esensi guru sebagai pendidik akan memperoleh dukungan lewat pembentukan mental kecendekiawanan guru.
Oleh M Sunyoto
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017