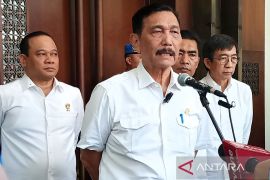Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
Indonesia Butuh 70 Stasiun Pemantauan Kualitas Udara
- Rabu, 1 Agustus 2007 16:31 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Utama Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Dr. Andi Eka Sakya menyebutkan Indonesia membutuhkan setidaknya 70 stasiun pemantauan kualitas udara yang harus didirikan di seluruh negeri.
Lebih lanjut ia menjelaskan saat ini BMG baru memiliki 37 stasiun pemantauan kualitas udara yang tersebar di 31 kota, yang enam di antaranya berada di ibukota Jakarta.
"Saat ini kita belum memiliki sistem pemantauan yang daya cakupnya nasional dan bekerja secara simultan," kata Andi di Jakarta, Rabu ketika menjelaskan tujuan seminar nasional BMG tentang pemantauan kualitas udara yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Ia menjelaskan BMG sedang berupaya menyusun rencana atau "cetak biru" upaya pemantauan kualitas udara yang lebih terintegrasi dengan berbagai pihak terkait, di antaranya dengan kalangan LSM, institusi pendidikan, dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH).
Cetak biru kebijakan pemantauan kualitas udara ini, ujar Andi, diharapkan bakal menjadi semacam pedoman buat rencana pembangunan.
"Karena data pemantauan nanti akan mengingatkan bagaimana seharusnya pembangunan dilakukan dan diprioritaskan. Data tidak cuma berakhir sebagai data, tapi juga jadi bahan pertimbangan," katanya.
Menurut dia, selama ini pemantauan kualitas udara di Indonesia tidak mendapat perhatian yang maksimal, terlebih ketika tsunami menghantam pada tahun 2004.
"Konsentrasi kita hanya untuk tsunami," katanya.
Masih kata Andi, hambatan memantau kualitas udara secara nasional selain masalah kurangnya stasiun pemantauan adalah keterbatasan alat analisis data, kawasan Indonesia yang sangat luas, dan kecenderungan polusi udara yang terus meningkat.
Bicara soal perkiraan biaya membangun tiap stasiun pemantauan udara, Andi menyebut kisaran angka Rp3 miliar. Biaya terbesar adalah untuk pengadaan alat yang masih harus diimpor.
Pada tahun 1996, Indonesia dipercaya menjadi satu dari 24 titik pemantauan kualitas udara dunia oleh Badan Meteorologi Dunia (WMO).
Stasiun pemantauan atmosfer global (GAW) itu dibangun di Bukit Kototabang, Sumatera Barat, dan menjadi barometer kondisi udara kawasan khatulistiwa dunia.
"Baru setelah 11 tahun dari itu, kita mulai mencoba menyusun cetak biru sistem pemantauan kualitas udara," kata Andi menyinggung seminar nasional tersebut.
Ini juga cerminan dari prioritas yang kurang mendukung fungsi BMG yaitu memantau kualitas udara, selain fungsi memantau meteorologi, geofisika, dan klimatologi atau iklim.
Melihat peta sebaran stasiun pemantauan kualitas udara BMG di seluruh Indonesia, diketahui bahwa semakin ke timur semakin jarang berdiri stasiun pemantau.
Di seluruh kawasan Irian misalnya cuma ada dua stasiun, bahkan di Maluku sama sekali tidak ada. Sedangkan di Jawa terdapat begitu banyak titik stasiun. Begitu pula dengan Kalimantan dan Sumatera.
Andi sendiri menilai sebaran itu sangat tidak optimal untuk memantau kondisi udara Indonesia, karena tiap kota tiap daerah punya kekhasan yang berbeda-beda.
"Seharusnya stasiun pemantauan kualitas udara diprioritaskan dibangun di kota-kota besar dan lokasi yang berpeluang terjadi tempat kebakaran hutan/lahan, supaya juga bisa menjadi dasar analisis kondisi udara di Indonesia secara lebih akurat sesuai runutan waktu," kata Andi.
Ia menekankan bahwa bila Indonesia memiliki data yang akurat dan berkesinambungan "Maka kita akan bisa menjelaskan kepada dunia tentang pelepasan karbon di Indonesia, tidak bakal seperti ini ... Kita dituduh menjadi pelepas karbon terbesar ketiga di dunia hanya karena kebakaran besar pada tahun 1997-1998".
Sementara itu, Kasubid Instrumentasi Klimatologi dan Kualitas Udara BMG, Tuti MHW mengaku hambatan terbesar saat ini untuk memantau kualitas udara Indonesia adalah proses pengiriman sampel data dari stasiun-stasiun di daerah.
"Alat timbang cuma ada di Jakarta, di kantor pusat BMG sehingga sampel-sampel itu dikirim dari stasiun di daerah. Kadang tiap hari, kadang tiap pekan, tapi ada juga yang setelah satu bulan baru dikirim ke Jakarta," kata Tuti.
Bila stasiun-stasiun pemantau udara yang berada di Jakarta sudah tergolong "canggih" dan otomatis, sehingga tidak perlu ditimbang lagi berat partikulat debu pada tiap meter kubiknya, alat-alat di stasiun di daerah justru semuanya manual.
"Itu sebabnya sampel penghitungan berat partikulat debu harus dikirim ke Jakarta, dan rata-rata baru diketahui hasilnya setelah dua pekan dari hari pemantauan," kata Tuti menambahkan.
Durasi dua pekan ini karena memang kebanyakan daerah baru mengirim sampel ke Jakarta setelah sampel dikumpulkan selama dua pekan, padahal proses penghitungan berat debu partikulat sangat cepat dan sederhana.
"Jalan keluarnya memang kalau tidak memperbaiki sistem pengiriman sampel ke Jakarta, atau melengkapi stasiun-stasiun pemantauan dengan alat timbang seperti yang ada di laboratorium di Jakarta," ujarnya.(*)