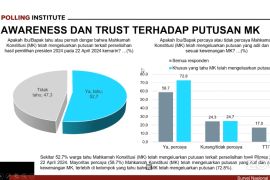Narasi politik dalam lima bulan ke depan memang tak jauh-jauh dari persoalan stabilitas dan persatuan. Semua elemen masyarakat layak diingatkan untuk waspada bahwa perebutan kursi kekuasaan puncak nasional yang digelar April tahun depan tak boleh mengguncang stabilitas dan mengoyak persatuan.
Di hari yang sama di tempat yang berbeda, kedua pemimpin nasional itu jelas punya pandangan yang muaranya searah dan setujuan bahwa pemilihan umum, ajang menentukan para pemimpin bangsa, adalah fase untuk memajukan bangsa dan menyejahterahkan rakyat.
Presiden Jokowi di hadapan 430 Komandan Resor Militer dan Komandan Distrik Militer se-Indonesia mengatakan stabilitas perlu dijaga bersama dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa mewujudkan stabilitas itu dengan menghadirkan rasa aman. Dalam konteks Pilpres 2019, sikap netral anggota TNI memiliki peran besar menjaga stabilitas.
Sementara itu, di hadapan pemimpin pemuda Muhammadiyah, Wapres Jusuf Kalla menekankan pentingnya sikap saling menghargai perbedaan-perbedaan pilihan politik. Sikap itu antara lain bisa diekspresikan oleh pemimpin organisasi masyarakat untuk tidak memaksakan anggotanya memilih capres-cawapres tertentu menyongsong Pilpres 2019.
Narasi stabilitas yang diangkat Jokowi memang krusial ketika suhu politik kian menghangat bahkan memanas seiring dengan semakin dekatnya tanggal pencoblosan. Lepasnya kendali aparat terhadap situasi sosial yang stabil jelas membahayakan demokrasi.
Efek lanjut atas hilangnya kendali terhadap stabilitas secara langsung akan mengoyak persatuan. Mudah untuk menfantasikan dampak destruktif macam apa yang akan terjadi jika prasyarat pembangunan itu, yakni stabilitas dan persatuan, terkoyak.
Itu sebabnya para cendekiawan, pemikir dan pengamat politik sejak awal mengimbau para elite politik untuk berkampanye dengan adu program dan bukannya mengusung propaganda politik identitas, terutama yang berbasis isu keagamaan.
Harus diakui bahwa usaha untuk menyeret nilai-nilai keagamaan ke dalam wacana politik menjelang perebutan kekuasaan sempat diisyaratkan oleh pendukung kedua kubu masing-masing pasangan capres-cawapres.
Namun dinamika politik yang dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai paradoks seperti preferensi pemilihan sosok ulama dalam pencapresan justru berdampak positif terhadap melemahnya gairah meningkatkan intensitas propaganda politik identitas.
Maka hadirlah situsasi politik berupa semakin gencarnya suara-suara dari aktivis prodemokrasi yang menyatakan bahwa penautan politik dan agama hanya mendestruksi demokrasi.
Sesungguhnya tak sulit untuk memahami kenapa perebutan kekuasaan berlangsung gegap gempita seolah jadi pertaruhan hidup mati para pendukung garis keras masing-masing kubu. Salah satu faktor yang mendorong hadirnya iklim semacam itu adalah pemegang kekuasaan di sini adalah pembuka akses bagi sumber-sumber politik dan ekonomi yang berpeluang untuk dieksploitasi, baik secara sah maupun korup.
Itulah sebabnya ikhtiar merebut kekuasaan cenderung dilakukan dengan segala cara, jika memungkinkan digunakanlah cara-cara yang tak etis, yang berisiko bahkan bagi persatuan bangsa, lewat cara-cara adu domba, memecah belah umat dan sebagainya.
Melalui tiga kali pengalaman pilpres secara langsung, yang berhasil dilewati rakyat tanpa terjadi perpecahan yang berarti, diharapkan pilpres secara langsung keempat pun terselenggara dengan aman, damai dan tentu saja demokratis.
Stabilitas dan persatuan tetap terjaga, terpelihara dengan faktor penentu utamanya adalah publik itu sendiri. Kenapa demikian? Sebab, ketika stabilitas dan persatuan itu lebih banyak diserahkan penjagaannya kepada aparat keamanan dan militer, seperti pengalaman traumatis di era otokratik sebelum Reformasi Mei 1998, kecenderungan ekses terjadinya pengerdilan demokrasi berpeluang hadir.
Terlalu tragis bila lepasnya kendali atas stabilitas dan terkoyaknya persatuan itu diakibatkan oleh pertarungan politik domestik di antara anak bangsa. Ketika situasi global saat ini berada dalam ancaman tekanan, baik oleh efek perang dagang negara raksasa penguasa ekonomi global maupun oleh ancaman ekologis yang kian mencemaskan, sinergi di antara anasir anak bangsa justru diperlukan.
Namun, yang juga tak kalah pentingnya untuk dicegah agar jangan sampai terjadi adalah persatuan oligarkhis di antara kaum elite politik akibat seruan untuk persatuan yang kelebihan dosis. Hal semacam ini sangat mungkin terjadi setelah pertarungan kekuasaan berlangsung. Pada poin ini, yang menjadi korban tak lain dan tak bukan adalah kepentingan publik yang tak masuk dalam lingkaran elite politik.
Di sinilah esensi politik, perjalanan dari perebutan kekuasaan yang dilewati dengan mempertahankan persatuan menuju fase pembagian kekuasaan di antara elite politik dengan menghindari oligarkhi politik yang memunggungi kepentingan publik. Para pengamat politik selalu mengingatkan perkara ini.
Untuk saat ini, saat menjelang Pilpres 2019, pertaruhannya memang jauh lebih besar ketimbang apa yang akan jadi kemungkinan untuk dikorbankan di momen setelah perhelatan perebutan kekuasaan terjadi.
Jika, yang dipertaruhkan saat ini di tengah suhu politik yang memanas selama kampanye adalah persatuan anak bangsa, begitu Pilpres berlalu dengan damai dan demokratis yang jadi pertaruhan adalah dilupakannya janji-janji politik yang ditebar selama masa kampanye.
Namun, dengan semakin berdaya dan tercerahkannya kekuatan sipil dan publik yang kian dewasa dalam berdemokrasi, kemungkinan-kemungkinan buruk itu bisa diminimalisasi, kalau bukan dihindari sama sekali.*
Baca juga: Gubernur: Wali Nagari dilarang dukung calon presiden
Baca juga: Haedar pastikan Muhammadiyah tetap berjarak dengan politik praktis
Pewarta: Mulyo Sunyoto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018